Nona Sempurna
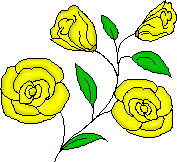 Dua minggu sebelum mudik, sebagian pikiranku sudah ada di rumah. Orang-orang terdekat juga tidak protes mendapati aku sering tidak klik dengan mereka. Sebab, ini memang gejala rutin yang muncul menjelang masa cuti.
Dua minggu sebelum mudik, sebagian pikiranku sudah ada di rumah. Orang-orang terdekat juga tidak protes mendapati aku sering tidak klik dengan mereka. Sebab, ini memang gejala rutin yang muncul menjelang masa cuti.
Aku selalu merasa ada yang kurang. Padahal, aku selalu membawa catatan kecil untuk memastikan semuanya beres menjelang dan seminggu setelah cuti. Tapi, tetap saja, aku seperti dikejar waktu. Persiapan Natal keluarga dan PAA terlihat kurang di sana sini. Padahal, rencananya sudah dipikirkan beberapa bulan sebelumnya.
Ini terjadi dari waktu ke waktu. Di puncak-puncak kekhawatiran acara tidak berjalan sesuai rencana, aku justru diingatkan untuk melupakan kesempurnaan. Selamat tinggal Nona Sempurna.
Kenapa?
Karena pulang kampung adalah kesempatan untuk menjadi anak kembali. Aku tidak perlu menjadi apapun. Aku hanya ingin menjadi anak dari ayah dan ibuku. Berbakti pada ayah dan ibuku dengan segala ketidaksempurnaanku.
Dua minggu memang terasa singkat untuk berbakti pada ayah dan ibuku. Karena itu aku merancang betul waktu buat teman-temanku. Cuma bertemu dua teman dalam waktu enam jam. Aku bahkan tidak mengunjungi apalagi menelepon sahabatku. Padahal, aku tahu betul dia ingin menunjukkan anak pertamanya. Selamat tinggal Nona Sempurna.
Tinggal jauh dari ayah dan ibu membuka mataku dari banyak hal. Termasuk benar-benar memanfaatkan waktu untuk mereka. Seminggu sebelum balik, kata-kata "Mah, mau minum teh?" terus berdengung di telingaku. Ya, itulah keinginanku. Aku ingin sekali membuat teh buat ayah dan ibuku setiap pagi, sore, atau kapanpun.
"Kok aku nggak pernah dibikinin teh," kakakku mengolok-olok. Aku tidak peduli. Sebab, dia pasti memprotes. Entah tehnya kurang gula atau kurang kental. Aku memang membuat teh buat ayah dan ibuku dengan sedikit gula dan teh kemasan yang dicelup sekejap. Ayah dan ibuku tidak akan protes. Sebaliknya, senang karena ada yang memperhatikan.
Bahkan, Ibuku selalu memuji sambal buatanku. Padahal, aku tahu persis bahwa itu untuk menyenangkan aku saja. Aku juga tahu diri, memang tidak pandai masak. Bukan karena aku nggak bisa (masak sih nggak bisa?). Tapi, di antara semua saudaraku aku yang memang tidak senang memasak dengan bumbu yang aneh-aneh itu. Kalau bisa semuanya rebus dan tanpa penyedap. Jadi, begitu aku masuk dapur, semua langsung berteriak. "Jangan. Jangan masak!"
Aku bahkan membiarkan Ibuku menyisir rambutku. Saudaraku tentu saja protes jika disisiri. Tapi, aku malah senang. Bahkan, Ibu juga yang memasak sendiri madu dengan lilin untuk mukaku. Sebaliknya, Ibuku juga membiarkan matanya aku "lukis" ketika akan ke pesta.
Ada satu lagi keinginanku yang belum kesampaian. Membersihkan gereja dengan teman-teman lingkungan atau menyempil dengan lingkungan yang lain. Mustinya aku bisa membersihkan gereja dengan lingkungan sepupuku, tapi nggak jadi. Tak masalah, good bye Nona Sempurna!
Rumah adalah sekolah paling baik bagi aku yang ingin semua serba teratur, rapi, sempurna. Apa sih kesempurnaan itu? Tak terukur. Aku tak bisa memaksakan definsi kesempurnaanku pada orang lain dan sebaliknya. Sebab, aku justru sering merasa sempurna karena ketidaksempurnaan orang lain dan sebaliknya orang lain merasa sempurna dengan memandang ketidaksempurnaanku. Jadi kenapa juga harus menjadi Nona Sempurna, jika itu justru membuat aku egois dan melakukan segala sesuatu dengan standar khas orang dewasa. Capek.
Aku tidak perlu malu karena tidak sempurna. Banyak kelemahan. Sebab hanya Allah yang sempurna. "...Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku (2 Korintus 12:9). Aku hanya ingin menjadi anak yang terus belajar menjadi sempurna dan terbuka untuk disempurnakan. Itu saja.
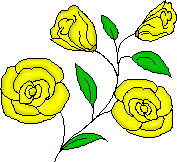 Dua minggu sebelum mudik, sebagian pikiranku sudah ada di rumah. Orang-orang terdekat juga tidak protes mendapati aku sering tidak klik dengan mereka. Sebab, ini memang gejala rutin yang muncul menjelang masa cuti.
Dua minggu sebelum mudik, sebagian pikiranku sudah ada di rumah. Orang-orang terdekat juga tidak protes mendapati aku sering tidak klik dengan mereka. Sebab, ini memang gejala rutin yang muncul menjelang masa cuti.
Aku selalu merasa ada yang kurang. Padahal, aku selalu membawa catatan kecil untuk memastikan semuanya beres menjelang dan seminggu setelah cuti. Tapi, tetap saja, aku seperti dikejar waktu. Persiapan Natal keluarga dan PAA terlihat kurang di sana sini. Padahal, rencananya sudah dipikirkan beberapa bulan sebelumnya.
Ini terjadi dari waktu ke waktu. Di puncak-puncak kekhawatiran acara tidak berjalan sesuai rencana, aku justru diingatkan untuk melupakan kesempurnaan. Selamat tinggal Nona Sempurna.
Kenapa?
Karena pulang kampung adalah kesempatan untuk menjadi anak kembali. Aku tidak perlu menjadi apapun. Aku hanya ingin menjadi anak dari ayah dan ibuku. Berbakti pada ayah dan ibuku dengan segala ketidaksempurnaanku.
Dua minggu memang terasa singkat untuk berbakti pada ayah dan ibuku. Karena itu aku merancang betul waktu buat teman-temanku. Cuma bertemu dua teman dalam waktu enam jam. Aku bahkan tidak mengunjungi apalagi menelepon sahabatku. Padahal, aku tahu betul dia ingin menunjukkan anak pertamanya. Selamat tinggal Nona Sempurna.
Tinggal jauh dari ayah dan ibu membuka mataku dari banyak hal. Termasuk benar-benar memanfaatkan waktu untuk mereka. Seminggu sebelum balik, kata-kata "Mah, mau minum teh?" terus berdengung di telingaku. Ya, itulah keinginanku. Aku ingin sekali membuat teh buat ayah dan ibuku setiap pagi, sore, atau kapanpun.
"Kok aku nggak pernah dibikinin teh," kakakku mengolok-olok. Aku tidak peduli. Sebab, dia pasti memprotes. Entah tehnya kurang gula atau kurang kental. Aku memang membuat teh buat ayah dan ibuku dengan sedikit gula dan teh kemasan yang dicelup sekejap. Ayah dan ibuku tidak akan protes. Sebaliknya, senang karena ada yang memperhatikan.
Bahkan, Ibuku selalu memuji sambal buatanku. Padahal, aku tahu persis bahwa itu untuk menyenangkan aku saja. Aku juga tahu diri, memang tidak pandai masak. Bukan karena aku nggak bisa (masak sih nggak bisa?). Tapi, di antara semua saudaraku aku yang memang tidak senang memasak dengan bumbu yang aneh-aneh itu. Kalau bisa semuanya rebus dan tanpa penyedap. Jadi, begitu aku masuk dapur, semua langsung berteriak. "Jangan. Jangan masak!"
Aku bahkan membiarkan Ibuku menyisir rambutku. Saudaraku tentu saja protes jika disisiri. Tapi, aku malah senang. Bahkan, Ibu juga yang memasak sendiri madu dengan lilin untuk mukaku. Sebaliknya, Ibuku juga membiarkan matanya aku "lukis" ketika akan ke pesta.
Ada satu lagi keinginanku yang belum kesampaian. Membersihkan gereja dengan teman-teman lingkungan atau menyempil dengan lingkungan yang lain. Mustinya aku bisa membersihkan gereja dengan lingkungan sepupuku, tapi nggak jadi. Tak masalah, good bye Nona Sempurna!
Rumah adalah sekolah paling baik bagi aku yang ingin semua serba teratur, rapi, sempurna. Apa sih kesempurnaan itu? Tak terukur. Aku tak bisa memaksakan definsi kesempurnaanku pada orang lain dan sebaliknya. Sebab, aku justru sering merasa sempurna karena ketidaksempurnaan orang lain dan sebaliknya orang lain merasa sempurna dengan memandang ketidaksempurnaanku. Jadi kenapa juga harus menjadi Nona Sempurna, jika itu justru membuat aku egois dan melakukan segala sesuatu dengan standar khas orang dewasa. Capek.
Aku tidak perlu malu karena tidak sempurna. Banyak kelemahan. Sebab hanya Allah yang sempurna. "...Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku (2 Korintus 12:9). Aku hanya ingin menjadi anak yang terus belajar menjadi sempurna dan terbuka untuk disempurnakan. Itu saja.




